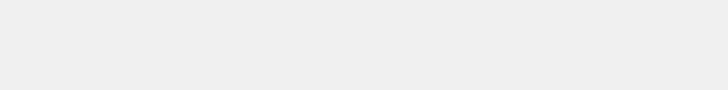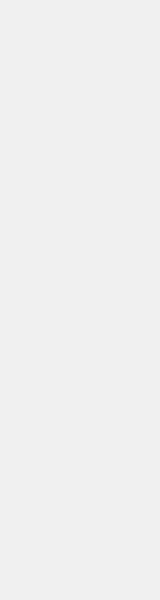:strip_icc()/kly-media-production/medias/5461576/original/034588900_1767422460-Kaspersky_Ungkap_31_Persen_Orang_Indonesia_Curhat_ke_AI_Saat_Sedih.jpg)
Survei terbaru oleh Kaspersky mengungkap bahwa 31 persen pengguna internet di Indonesia memilih untuk mencurahkan isi hati kepada kecerdasan buatan (AI) saat merasa sedih atau tidak bahagia, sebuah angka yang melampaui rata-rata global sebesar 29 persen. Fenomena ini, yang kian menonjol di kalangan Generasi Z dan milenial (35 persen) dibandingkan kelompok usia di atas 55 tahun (19 persen), menandai pergeseran signifikan dalam pencarian dukungan emosional di tengah masyarakat digital Indonesia.
Pemanfaatan AI sebagai teman curhat mencuat karena kemudahan akses, biaya rendah, dan minimnya risiko sosial yang sering menyertai interaksi manusia. Afinnisa Rasyida, M.Psi., dosen Program Pendidikan Profesi Psikologi Universitas Surabaya (Ubaya), menyatakan bahwa perilaku mencari bantuan dipengaruhi oleh faktor personal, sosial, dan struktural, termasuk rasa takut akan stigma, kendala biaya, atau keterbatasan layanan profesional. Ia mengidentifikasi AI sebagai alternatif yang mudah dijangkau. Mashita Phitaloka Fandia Purwaningtyas, SIP, MA, pakar Ilmu Komunikasi UGM, menggarisbawahi bahwa kondisi sosial akibat kapitalisme modern sering memperparah kesepian dan keterasingan, terutama di lingkungan perkotaan yang serba cepat dan kompetitif, menjadikan AI tawaran hubungan yang lebih sederhana tanpa tuntutan.
Namun, para ahli psikologi memperingatkan terhadap ketergantungan dan keterbatasan AI dalam memberikan dukungan emosional yang substansial. Profesor Dr. Rose Mini Agoes Salim M.Psi., Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, mengingatkan bahwa meskipun respons AI mungkin terdengar akurat, kesesuaiannya dengan kondisi spesifik individu perlu dipertanyakan. Jawaban AI, yang bersandar pada basis data serupa, berpotensi menjadi standar umum dan gagal memahami konteks mendalam atau aspek kepribadian yang kompleks. Psikolog klinis Phoebe Ramadina, M.Psi., dari Universitas Indonesia, menyoroti risiko jangka panjang seperti kurangnya kemampuan sosial-emosional, ekspektasi tidak realistis terhadap interaksi, dan peningkatan rasa kesepian akibat alienasi dari interaksi sosial nyata. Ia menegaskan bahwa interaksi dengan AI dapat menimbulkan ketergantungan dan mengurangi minat seseorang untuk berhubungan dengan manusia di dunia nyata.
Meskipun AI dapat berfungsi sebagai alat bantu awal untuk mengelola stres ringan, berpikir berlebihan, atau refleksi diri, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran tenaga profesional kesehatan mental seperti psikolog. AI memiliki keterbatasan dalam membangun empati, menciptakan hubungan emosional, atau menangkap kompleksitas kebutuhan konseli yang bersifat kontekstual dan personal. Responden survei Kaspersky sendiri juga menyuarakan kekhawatiran terkait privasi data dan potensi ketergantungan emosional pada AI. Para ahli Kaspersky juga mengingatkan pentingnya skeptisisme terhadap saran AI dan kehati-hatian dalam membagikan data sensitif karena sebagian besar chatbot dimiliki oleh perusahaan komersial dengan kebijakan pengumpulan dan pemrosesan data mereka sendiri.
Penggunaan AI untuk dukungan emosional memang menawarkan akses 24/7 dan anonimitas bagi individu yang enggan mencari bantuan profesional secara langsung. Ini berpotensi membantu dalam identifikasi dini gejala gangguan mental dan menyediakan informasi yang relevan. Namun, masa depan integrasi AI dalam kesehatan mental Indonesia memerlukan kerangka regulasi dan etika yang jelas. Ini esensial untuk memastikan perlindungan data pribadi dan mengatasi tantangan yang muncul, sehingga pemanfaatan AI benar-benar dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan kesejahteraan psikologis dan kapasitas individu untuk berinteraksi secara autentik dengan sesamanya.